Siapa Membunuh Putri (6) - Ajakan Bang Jon

Ilustrasi lulusan terbaik Polri yang dicopot lantaran terseret kasus Ferdy Sambo-Unsplash/ Logan Weaver -Unsplash/ Logan Weaver
BANG Jon menolak bertemu sehabis rapat itu. Ia bilang besok pagi saja. Saya lihat wajah putihnya – putih khas orang Manado yang rada mirip Tionghoa itu, juga sempit bukaan matanya itu – tak lagi memerah seperti di tengah rapat redaksi tadi. Saya agak tenang melihatnya. ”Besok di Kedai Purnama, ya. Tahu kan?”
Aku langsung tancap gas di ruang redaksi. Dua redaktur yang membantu tak perlu diragukan kerjanya. Stok berita cukup. Bayangan headline halaman depan dan semua halaman dalam sudah ada juga. Saya masih ada waktu mengetik beritaku sendiri. Lalu menyunting hasil wawancara wartawan kami dengan pejabat di Otoritas Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas. Atau OPKPB . Orang di kota ini bisa menyebut OP saja. Metro Kriminal, seperti media lain, juga biasa menyebut dengan ringkasan OP saja. Soal investasi besar, Maestrochip Corp. yang akan menyerap sepuluh ribu pekerja. Angka yang luar biasa besar.
Saat aku mengedit berita itu, Bang Eel tiba di kantor. Dia langsung bertanya padaku. ”Dur, ada berita dari OP soal investasi Maestrochip Corp?”
"Ini sedang saya edit, Bang.”
Bang Eel, menggeser dudukku, mengambil alih komputer yang kupakai mengedit, mengecek judul, membaca lead, dan dengan cepat men-scroll layar sampai ke akhir berita.
”Oke, ini nanti di halaman depan, ya,” katanya.
”Cocok, Bang? Kita koran kriminal lo? Apa gak aneh?”
”HL kedua, bukan headline utama. Ini perusahaan besar, bakal menyerap sepuluh ribu operator, Dur. Nanti mereka pasang iklan loker tiap hari. Ini Bang Ameng yang pegang semacam humasnya atau penghubungnya di lokal. Ia yang pegang dan atur iklannya. Ia akan sering kontak kau nanti. Temui aja. Langsung. Tak usah sama-sama aku, tak apa. Kau kan sudah kukenalkan….”
Aku belum terlalu paham.
”Sudah, saving dulu. Nanti hilang. Belum ada kerjaan lain? Semua aman kan? Rapat tadi gimana?”
”Aman, Bang…”
”Bagus, kau tegas saja sama Jon itu. Tadi aku sudah tahu, kok. Mila tadi telepon aku ke percetakan,” kata Bang Eel.
Bang Eel ajak saya bicara di ruangannya. Dia mau sampaikan hasil rapat dengan orang percetakan. Intinya, Surabaya akan kirim mesin cetak baru, lebih cepat, lebih bagus hasilnya, bisa maksimal enam belas halaman sekali jalan. Dua tower istilahnya. Tapi Metro Kriminal harus mencapai 30 ribu. ”Minimal 20 ribulah. Kalau lihat tren kenaikan beberapa bulan terakhir, kita bisa akhir bulan ini tembus 20 ribu,” kata Bang Eel.
Dia seperti menuntut, memicu, dan menyemangati saya. ”Mesin yang sekarang akan dikirim ke Medan. Tadinya mesin baru itu untuk di Medan sana,” kata Bang Eel. Saya mengiyakan saja. Tampak berat tapi menantang. Kalau harus tambah halaman, saya sudah menghitung tenaga redaksi pasti kurang.
”Kalau tercapai 20 ribu kita boleh nambah wartawan,” kata Bang Eel. Dengan janji dukungan seperti itu rasanya saya bisa optimistis. Ia juga cerita tentang rencana grup kami bikin koran kedua. Bahkan namanya pun sudah ada. ”Dinamika Kota”. Koran umum, bukan koran kriminal seperti Metro Kriminal.
***
Kedai Kopi Purnama namanya. Nama yang melegenda. Sudah beberapa kali aku ngopi dan, nah ini dia, menyantap hidangan khas mie lendir. Kalau dengar namanya rasanya agak jijik. Kata lendir itu konotasinya memang kotor, dan jorok. Kata itu merujuk ke kuah kacang yang dikentalkan dengan tapioka. Ya, memang seperti lendir jadinya. Tapi itulah nikmatnya. Kuah dengan aroma ebi, dan gurih kaldu, melimpah di atas mie yang silindernya besar-besar.
Bang Jon sudah menunggu ketika aku tiba di kedai itu. Dengan rokok putih mahal. Dua bungkus dia tumpuk di meja di hadapannya, di sebelah kunci Storm. Di tangannya Zippo perak yang ia buka-tutup, ia nyala-hidupkan.
”Minum apa, Dur? Kopi tarik? Atau teh tarik?” Aku memesan teh tarik.
Tandas seporsi mie lendir. Bang Jon menawari pesan makanan lain. Saya bilang itu sudah cukup. ”Bungkus ya, buat anak-anak panti?” tanya Bang Jon. ”Koh, bungkus ya… Ke sinilah, ini tanya kawan saya ini, berapa bungkus,” katanya memanggil koko kedai kopi.
”Nggak ngerokok, Dur? Ini coba. Enak lo…,” kata Bang Jon. Saya coba sebatang. Saya tak tahu bagaimana rasa rokok enak dan tidak enak. Bagiku sama saja. Bikin dinding mulut terasa tebal dan tenggorokan langsung gatal kayak mau batuk. Jon terkekeh-kekeh.
”Kamu masih di panti asuhan itu ya? Ambil rumahlah. Itu ada perumahan baru ke arah bandara,” kata Bang Jon.
”Belum punya uang mukanya, Bang,” kataku.
”Uang muka kok dipikir,” kata Bang Jon. ”Nah, gini. Mumpung kita lagi omongin uang. Aku ajak kamu ngomong ini.” Dia perbaiki posisi duduk. Menegakkan tubuh, menandai keseriusannya. Agak heran juga saya dengan keramahannya, apalagi teringat kemarahannya kemarin sebelum dan pada saat rapat.
Bang Jon lalu cerita soal rencana grup Pedoman Rakyat. Saya tahu itu grup media besar, lebih besar, dan lebih tua dari grup koran kami. Grup itu akan buka koran di kota kami.
”Aku sudah ketemu mereka, Dur,” kata Jon. ”Aku mau tahu sekarang berapa gaji barumu?”
Saya bisa menebak ke mana arah pertanyaan Bang Jon, saya sebutkan saja angka di SK baru itu.
”Kamu mau ikut aku nggak? Kita gabung ke koran Grup PR itu, namanya bagus Podium Kota, bukan koran kriminal. Capek kita di kriminal terus. Itu koran sudah ada di beberapa kota. Bakal jadi pesaing grup kita. Di beberapa kota lain, grup kita goyang, Dur. Mereka serius. Dipersiapkan benar. Juga soal gaji wartawan. Jauh lebih baik. Saya bisa pastikan gajimu di koran baru itu bisa dua kali lipat minimal. Terserah kami minta berapa, asal tak lebih dari tiga kali lipat gajimu sebagai asredpel yang kamu sebut tadi itu,” kata Jon.
Saya sangat terkejut dengan tawaran Bang Jon ini. Begitu cepatnya sikap Bang Jon berubah. Ada apa? Apakah persaingan dengan Bang Eel kini juga bersaing memperebutkan aku agar ada di pihak mereka, bahkan kini tawarannya adalah berada di koran yang berbeda? Tapi rasanya aku tak sepenting itu untuk diperebutkan.
Saya mematikan rokok. Menunduk. Tak tahu bagaimana hendak menolak. Juga sangat ragu untuk menerima. Dalam banyak hal, grup PR di mata orang banyak, di negeri ini, lebih baik dari grup koran kami. Grup kami memang lekas sekali berkembang. Seakan-akan tanpa perhitungan bisnis yang matang. Intuitif saja.
Mitos yang dipercaya orang, katanya, Indroyono Idris, CEO grup kami itu, kalau mau bikin koran cukup lihat apakah di kota itu ada ATM BCA. Kalau ada berarti layak buka koran. Kelak saya bertemu dengannya, saya tanyakan mitos itu. Tapi logikanya mudah saja, BCA tentu tak sembarang buka cabang. Pasti sudah dengan survei dan kajian perputaran uang yang cukup untuk sebuah cabang bank mereka.
Grup PR sebaliknya amat berhati-hati mengembangkan koran-koran di daerah. Pakai survei dan riset yang makan waktu lama.
Bang Jon meletakkan dua pilihan di hadapanku: bergabung di grup yang besar, mapan, dan legendaris itu, atau tetap di grup kami yang muda, agresif, dan baru saja memberiku sebuah kenaikan posisi karir yang amat lekas kuraih.
”Kau jawab besok saja, tak usah hari ini. Eh, tapi aku hari ini dan besok izin tak masuk ya. Sudah bertahun-tahun kayaknya aku ndak pernah cuti,… Bilang sama Eel ya, aku izin, malas aku hubungi dia,” kata Bang Jon.
Seorang perempuan manis sekali, menghampiri kami setelah dilambai oleh Bang Jon. Dia diperkenalkan sebagai Nenia. ”Ini lho, Si Abdur yang sering kuceritakan kamu. Yang kode beritanya ‘dur’ itu,” kata Bang Jon.
Nenia datang, mendekat seperti cahaya terang dan mengubah aroma kopi dan teh dari uang air panas dari tempat penyeduhan itu jadi wangi. Menyapa merdu, dan menjabat dengan lembut.
Tapi gelombang menimbang hal-hal besar, pilihan-pilihan yang menentukan langkah dan masa depan menderu, menggempur dinding-dinding benakku. Bertahan pada posisi bagus yang baru saja kuterima atau menerima tawaran posisi yang lebih baik dengan imbalan yang jauh lebih baik? (Hasan Aspahani-bersambung)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:





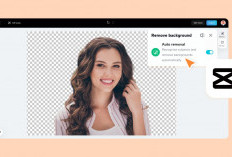










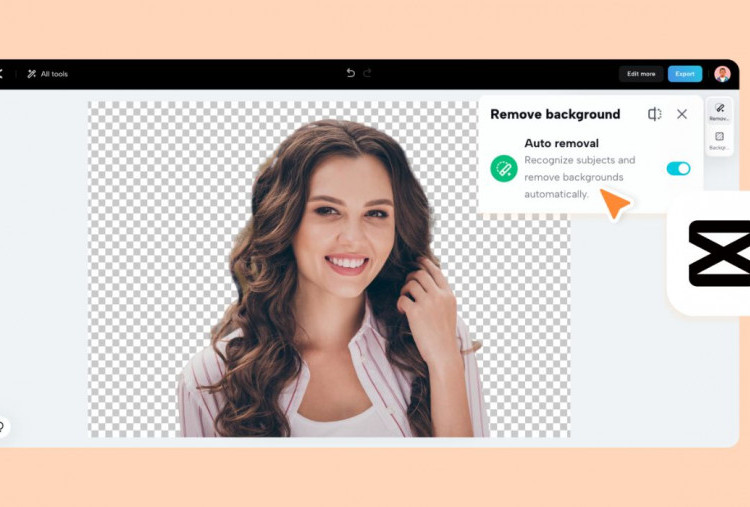

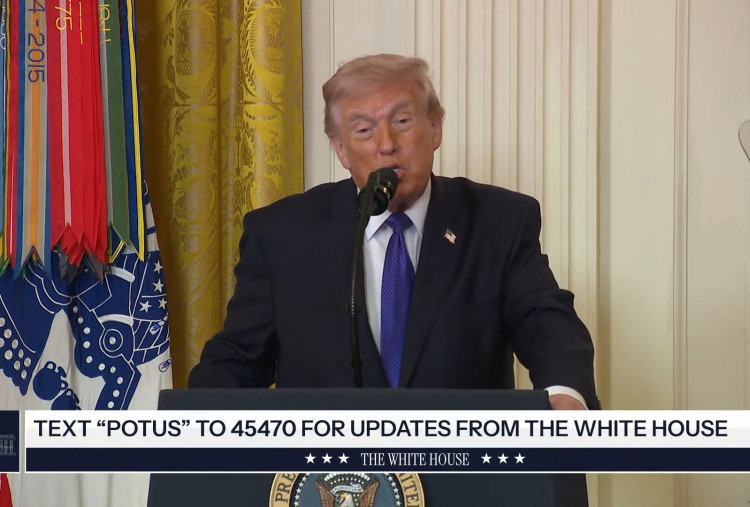



Komentar: 22
Silahkan login untuk berkomentar