Kepercayaan Koran

SAYA tidak bisa marah. Apalagi menolaknya: hasil penelitian itu. Bahwa kepercayaan masyarakat kepada koran ternyata tidak lebih tinggi dibanding kepada medsos.
Dari 1.020 responden, 32 persen mengatakan tidak percaya pada koran. Angka itu kurang lebih sama terhadap medsos. Atau terhadap televisi.
Berita baiknya: 30 persen masyarakat tidak percaya pada media. Apa saja. Berarti masyarakat sudah lebih independen.
Kabar buruknya: kepercayaan pada media online meningkat. Kepercayaan pada surat kabar menurun.
Itu kabar buruk bagi saya saja. Bukan bagi Anda.
Tahun lalu saya ngotot mendirikan media cetak: Harian Disway. Di Surabaya. Asumsi saya: jurnalisme media cetak akan lebih baik dari jurnalisme online. Dengan demikian media cetak bisa lebih dipercaya.
Hasil penelitian itu seperti menohok saya. Itulah penelitian yang dilakukan Dewan Pers bekerja sama dengan Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Jakarta. Yang pokok-pokok hasilnya dibeberkan Hendry Ch Bangun dari Dewan Pers.
Kemarin, Serikat Penerbit Pers (SPS) berulang tahun ke-75. Ditandai dengan Zoominar. Bukan saya lagi ketua umumnya. Saya hanya jadi salah satu pembicara.
Saya terkaget-kaget ketika Bangun menampilkan angka-angka penelitian itu.
Yang juga menarik adalah: mengapa mereka tidak percaya pada koran. Hampir 40 persen mengatakan beritanya tidak bisa dipercaya. Koran itu juga dinilai partisan. Dan wartawannya kurang kompeten.
Berita baiknya: itu pula yang menjadi alasan mengapa responden tidak percaya pada berita medsos dan TV.
"Kepercayaan pada online meningkat sedikit menjadi 42 persen. Kepercayaan kepada koran menurun menjadi 37 persen," ujar Bangun yang baru saja pensiun dari Kompas.
Jurnalisme koran ternyata dianggap tidak lebih baik dari online dan TV. Bahkan koran dianggap sama saja: sering menampilkan berita hanya dari satu sumber berita.
Selama ini saya berasumsi hanya media online yang menulis berita dari satu sumber. Wartawan tahu: itu tidak baik. Tapi wartawan juga maklum: kan online. Yang penting harus cepat upload. Sumber berita satunya bisa saja di-upload beberapa detik kemudian.
Ternyata berita koran juga sudah dianggap seperti itu. Cilaka! "Penyakit online" ternyata dianggap sudah menular luas ke media cetak.
Kalau hasil riset mengatakan seperti itu mau apa lagi: koran benar-benar kehabisan harapan.
Orang seperti saya berharap, lama-lama orang akan memilih: media apa yang bisa dipercaya. Lalu pilihan jatuh ke media cetak.
Ternyata salah!
Ternyata persepsi masyarakat sudah menyamakan reputasi jurnalisme koran dengan online. Sama rendahnya.
Kalau kenyataannya seperti itu maka bukan hanya koran yang akan mati. Juga jurnalisme itu sendiri.
"Apakah koran masih bisa hidup?" tanya salah seorang peserta Zoominar.
Dulu, saya menjawab dengan gagah: masih bisa hidup. Sampai kapan pun.
Kemarin saya menjawab: tidak bisa hidup lagi. Kalau toh ada yang masih bisa hidup –seperti di daerah-daerah– itu sekadar hidup. Bukan hidup yang bisa membiayai lahirnya jurnalisme yang ideal.
Saya sebenarnya berharap media cetak akan menjadi penyelamat jurnalisme yang baik. Bahkan sampai saya sebut ''jurnalisme media cetak akan menjadi kasta tertinggi dalam jurnalisme''.
Dari paparan hasil riset kemarin, omongan saya itu menjadi omong kosong. Kecuali, ada usaha yang serius untuk menyelamatkan jurnalisme. Usaha penyelamatan itu pasti tidak bisa dilahirkan oleh media partisan –termasuk partisan perusahaan umum.
Hasil penelitian itu melahirkan kesan pada diri saya: kepercayaan kepada koran sudah hancur. Padahal bisnis jurnalisme adalah bisnis kepercayaan.
"Apakah tidak bisa diselamatkan?" tanya peserta lainnya.
"Bisa, tapi lama" kata saya. Itu harus dimulai dari usaha membangun kembali kepercayaan kepada koran. Belum tentu memulihkan barang rusak seperti itu bisa berhasil dalam lima tahun.
Salah satu jalan keluar diberikan juga oleh Januar Ruswita, ketua Harian SPS Pusat: koran beralih ke platform digital, tapi semangatnya harus tetap semangat koran.
Tapi ketika ditanya operasionalnya seperti apa, memang belum ditemukan. Sebab, sampai sekarang pun, media cetak yang sudah masuk digital juga belum ada yang sukses.
Hasil riset itu juga menyebut 60 persen responden hanya mau mengikuti media yang gratis. Hanya 10 persen yang mau bayar. Selebihnya tidak tegas.
Disway sendiri pernah melakukan penelitian kecil-kecilan: apakah masih mau membaca Disway kalau harus berbayar.
Hasilnya, Anda sudah tahu: Disway tetap tidak berbayar. (Dahlan Iskan)
---
Komentar Pilihan Disway di artikel berjudul Luhut Merit
Robban Batang
Orang sibuk :pintar atur waktu.Pengangguran ,kurang kerjaan tapi mengeluh selalu kehabisan waktu.
Dari kampung
Yg menempati puncak lonceng adalah pegawai biasa² aja yg "ada lu gak lebih, gak ada lu gak kurang".
Iman Akhir
Seratus persen perasan saya terwakili oleh tulisan abah kali ini.. tahunan kerja dikasih tugas ini itu.. tapi saya memang bukan opung luhut.. jadi di akhir akhir karir saya bikin ulah jadi orang yg paling bermasalah biar cepat bebas dari tugas n cepat dapat pesangon..
Kliwon
Waduh, aku tinggal mbecak bentar aja udah ada keramaian. Jadi inget petuah guru aerobikku dulu, "Jika kamu tak mampu meyakinkan orang dengan kepintaranmu, maka bingungkanlah dia dengan kebodohanmu." Jadi begitulah. Tiap hari ilmu itu aku amalkan sambil wiridan (wira wiri turut dalan)
Dodol Surodol
ini antitesis sekali dengan prinsipnya Mukidi dan juga kebanyakan kita.. Kalau orang lain bisa kenapa harus saya Kalau orang lain gak bisa ya apalagi saya hehehe... sehat selalu bah..
Manto Simare-mare
Super sekaliiiii... Tambah satu ungkapan ya om "Kehebatan anda, bukan diukur seberapa banyak tugas yg anda terima, tapi seberapa bagus anda melakukan tugas itu..."
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:


















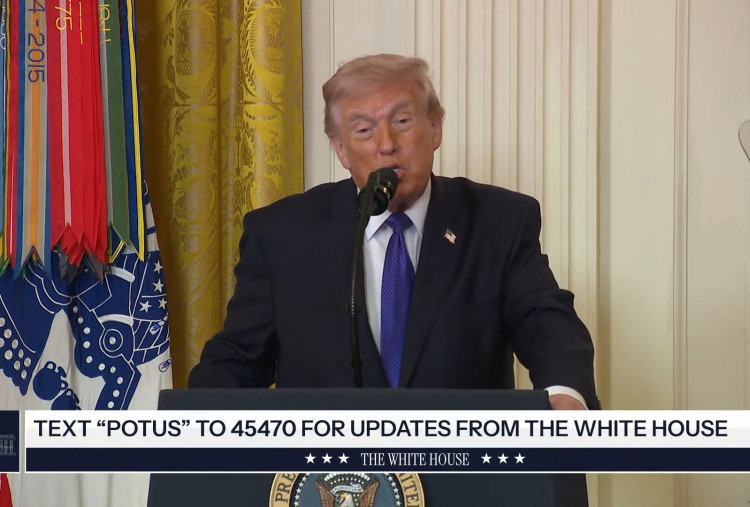

Komentar: 402
Silahkan login untuk berkomentar