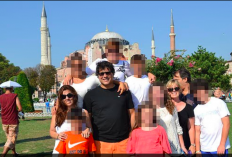NU, Organisasi dan Arogansi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam sebuah kegiatan ulama belum lama ini.-ist-
DI SEBUAH tikungan sejarah, ketika angin transformasi bertiup kencang, Nahdlatul Ulama, rumah besar para kiai dan umat, berdiri di persimpangan jalan. Ia mungkin ibarat perahu tua yang sarat makna, mengarungi zaman dengan petuah "tawassuth" (moderat) dan "tasamuh" (toleran).
Namun belakangan, nahkoda di pusat kemudi seolah lupa akan kompas kearifan itu. Sebuah bayang-bayang baru membentang: sentralisme yang dingin, nyaris militeristik, melingkupi denyut nadi organisasi khidmah ini.
Dalam sejarahnya, pada mulanya, NU adalah himpunan para kiai pesantren atau setidaknya dari lembaga pendidikan diniyah, sebuah majelis ilmu, dengan akar rumput yang hidup dari kesederhanaan dan ketulusan.
BACA JUGA:Yang Ilahi dan Yang Insani di Jalan Kramat
Kini, ia juga sebuah organisasi raksasa, dengan struktur yang menjangkau desa-desa. Struktur, bagaimanapun, mensyaratkan aturan, dan aturan sering kali berhadapan dengan "kuasa".
Kita melihat bagaimana PBNU hasil Muktamar Lampung ke 34, dalam beberapa waktu terakhir, seolah bertangan besi dan memegang palu godam organisasi. Bukan sekadar menegakkan disiplin, tapi juga, dalam pandangan beberapa pihak, menabrak tradisi musyawarah.
Ada PWNU dan PCNU yang dikarteker. Ada hasil konferwil dan konfercab yang dibatalkan, ditolak, bahkan pengurusnya dipecat. Di Makassar, di Karawang, di Jombang, dan entah di mana lagi, suara "akar rumput" yang termanifestasi dalam keputusan konfercab seolah menguap di hadapan keputusan pusat.
Kuasa, tentu saja, diperlukan dalam organisasi sebesar NU. Tanpa itu, struktur bisa runtuh. Namun, ketika kuasa itu digunakan untuk membatalkan suara dari bawah secara sepihak, tanpa proses klarifikasi yang memadai, ia mulai terasa seperti arogansi. Para kiai di daerah meradang. Mereka merasa proses demokrasi internal yang mereka jalani, sesuai AD/ART, diabaikan begitu saja.
BACA JUGA:Enam Alasan Kuat Gus Zulfa Layak Mengemban Amanah (Pjs) Ketua Umum PBNU
Fenomena ini mengingatkan kita pada ironi sebuah institusi yang lahir dari semangat menolak penjajahan dan membela kedaulatan, kini bergulat dengan isu "penjajahan" internal dalam bentuk sentralisasi kuasa yang berlebihan.
Dalihnya mungkin efisiensi, atau mungkin penyelamatan organisasi dari konflik lokal. Tapi, bukankah konflik lokal seharusnya diselesaikan secara lokal, dengan kearifan yang juga lokal?
Ketika PBNU menunjuk karteker, mandat utamanya sering kali adalah menyelenggarakan konferensi ulang. Namun, dalam beberapa kasus, mandat itu terkatung-katung, atau keputusan kartekernya sendiri ditolak oleh mayoritas MWC.
Ini menunjukkan adanya keretakan komunikasi, atau yang lebih parah, krisis kepercayaan. NU, dengan segala kebesarannya, selalu mengajarkan tawasuth (moderat) dan tasamuh (toleransi). Nilai-nilai ini seharusnya juga berlaku dalam berorganisasi secara internal.
BACA JUGA:Indonesia, Rumah Baru Islam Dunia: Cerita dari Kampus UIII
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: