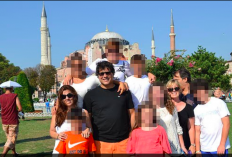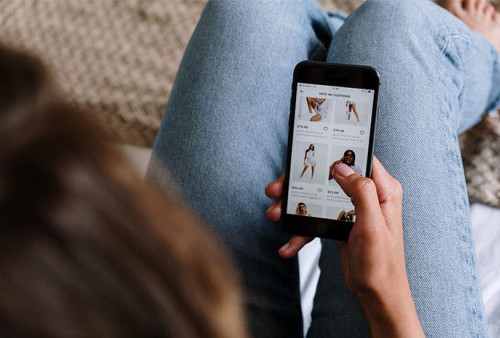Ihwal Tafsir Peraturan, Kuasa, dan Sebuah Jalan Tengah

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menanggapi kabar pemberhentiannya oleh Syuriyah PBNU-disway.id/Fajar Ilman-
ENTAH dari mana kita harus memulai, sebab kegaduhan ini nampaknya belum akan reda, Sekjen dan Bendum akhirnya digeser oleh Ketua Umum yang sudah dianggap "tak berwenang" versi Syuriah, jadi seperti kerikil yang dilempar ke kolam, riaknya meluas tanpa henti.
Ini bukan sekadar soal administrasi organisasi, atau tafsir kaku pasal-pasal dalam AD/ART dan Peraturan Perkumpulan semata, tapi soal marwah, soal kepemimpinan, dan—barangkali yang paling penting—soal bagaimana kita mendefinisikan otoritas dalam sebuah jam'iyah ulama yang berumur satu abad ini.
BACA JUGA:Indonesia dan Diplomasi Moral Dunia
Dan, yang gaduh, jika boleh dibilang begitu, adalah tafsir "pijakan" yang saling berbenturan dari dua kutub otoritas di PBNU. Di satu sisi, ada Gus Yahya, Ketua Umum Tanfidziyah, yang berpijak pada legitimasi Muktamar dan AD/ART sebagai landasan formal tertinggi, menolak gagasan pemberhentian di tengah jalan kecuali melalui mekanisme Muktamar.
Beliau kekeh, bersikukuh dan mengklaim keputusan Syuriyah tidak sah secara prosedural karena juga Syuriah tidak melibatkan dirinya dalam proses klarifikasi, dan menyebutnya "batil menurut syariat" karena melanggar prinsip keadilan.
Di sisi lain, Syuriyah, yang dipimpin Rais Aam, berargumen bahwa mereka adalah pimpinan tertinggi dan memiliki wewenang mengawasi dan memutuskan, berbekal Peraturan Perkumpulan (produk Konbes yang juga legal) sebagai tafsir pelengkap pasal-pasal AD/ART yang dianggap masih global.
Bagi Syuriyah, tindakan mereka adalah bagian dari menjaga marwah organisasi dan meluruskan dugaan pelanggaran etika dan tata kelola, dan persoalan ini harus diselesaikan melalui Majelis Tahkim jika ada keberatan.
Padahal idealnya dua pijakan di atas saling melengkapi, yang satu petunjuk global yang satunya lebih detail dan rinci. Tapi karena "sengkarut," maka masing-masing kubu seperti membawa satu pecahan atau potongan cermin dan melihat bayangan "kebenaran" dirinya dalam pecahan atau potongan cermin itu.
BACA JUGA:Langkah Bijaksana Syuriah dan Rais Aam PBNU
Bukankah seharusnya potongan dua cermin yang pecah itu disatukan kembali? Supaya utuh kita melihatnya. Ada yang global, lalu ada yang rinci? Supaya sudut pandang fiqih --pegangan nahdliyin--- dalam polemik ini juga bisa digunakan? Fiqih, dalam tradisi NU, bukan sekadar seperangkat hukum mati, tapi sebuah metode berpikir yang lentur, yang mengedepankan kemaslahatan (maslahah mursalah) dan menolak kerusakan (mafsadah).
Jalan tengah (tawassut) yang diajarkan para kiai adalah jalan islah (perdamaian), bukan saling klaim legitimasi yang berujung pada faksionalisasi permanen. Polemik ini, dari kacamata fiqih, supaya tidak menjadi fitnah (ujian/kekacauan).
Prinsip sadd al-dzarī'ah (pencegahan kerusakan) menuntut agar para elite PBNU menghentikan penyebaran informasi yang kian memperkeruh suasana dan duduk bersama.
Majelis Tahkim telah disiapkan sebagai mekanisme internal untuk menyelesaikan perselisihan ini, sebuah ruang yang didesain agar masalah diselesaikan dengan "cara ulama".
Supaya lagi, nahdliyin di akar rumput, tidak terseret dalam narasi provokatif atau berpihak secara membabi buta dan bisa mengedepankan husnuzan (prasangka baik) bahwa kedua belah pihak, dengan caranya masing-masing, sedang berjuang untuk NU.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: