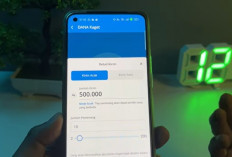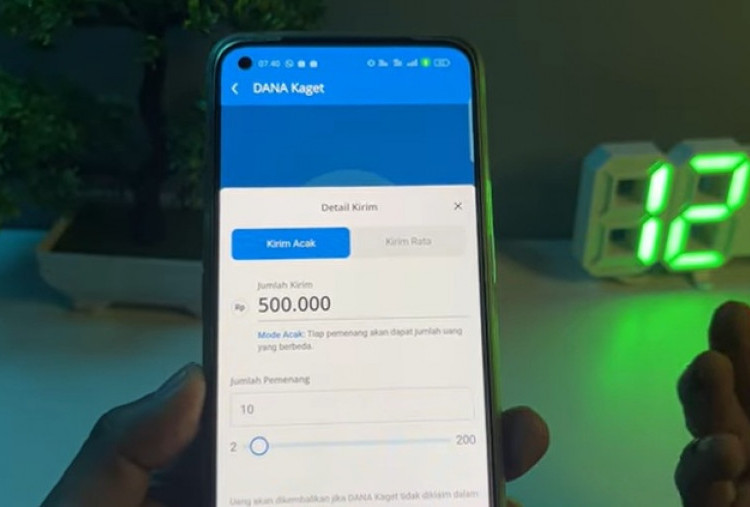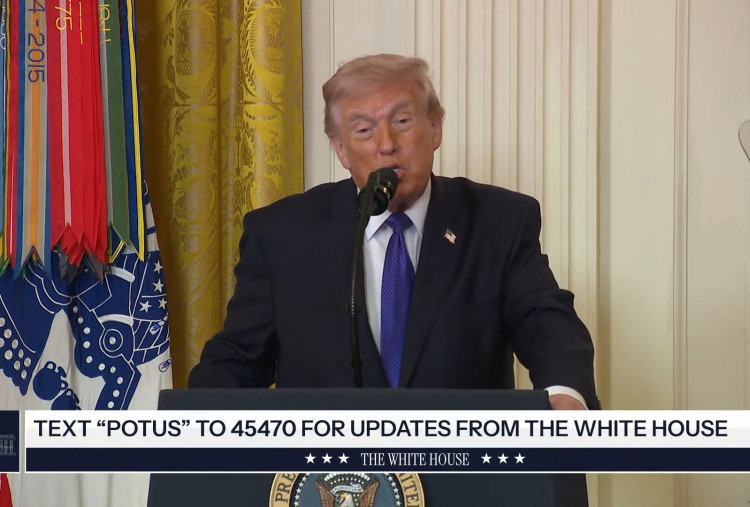Ibnu Athaillah, Nasihat Sufistik untuk Umat dan Penguasa

KH Imam Jazuli Lc--
SEORANG sufi besar lahir di Iskandaria, Mesir, pada abad 13 (658 H./1620 M.), bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha'illah al-Judzami. Ia yang dikenal sebagai Ibnu Athaillah, yang memiliki kemiripan dengan kakeknya, Syeikh Abu Muhammad Abdul Karim. Sejak kecil menekuni ilmu fikih mazhab Maliki, dan sebagai salah satu pilar Tarekat Syadziliah. Dalam usianya yang cukup muda (49), Ibnu Athaillah as-Sakandari wafat pada tahun 1309.
Di awal perjalanan intelektualnya, Ibnu Athaillah adalah orang yang ingkar pada ilmu tasawuf. Ia pernah berkata begini: "barang siapa yang bilang ada ilmu lain selain ilmu kita (fikih), maka ia sudah berbuat dusta pada Allah swt" (Muhannad Syawqi Abdali, al-Isyarat al-Kalamiah fi al-Hikam al-'Athaiyah, Dar al-Khalij li Nashr wa Tawzi', Amman, 2020: 24).
Namun, sejak bersahabat dan belajar kepada Abul Abbas al-Mursi, Ibnu Athaillah menyadari kekurangan pengetahuannya. Ia pun menyesali kata-katanya sendiri, dan berkata: “aku kini tertawa kalau ingat kata-kataku yang pertama”. Abul Abbas al-Mursi pun berwasiat kepada Ibnu Athaillah, “tetaplah pegang ajaran ini. Nantinya engkau akan menjadi pemimpin dalam dua mazhab; syariat dan tasawuf,” (Muhannad Syawqi Abdali, 2020: 24).
Selama menekuni ilmu tasawuf, Ibnu Athaillah banyak melahirkan karya, antara lain: Lathaiful Minan fi Manaqib Syeikh Abil Abbas wa Syaikhihi Abil Hasan, al-Qashdu al-Mujarrad fi Ma'rifat al-Ism al-Mufrad, At-Tanwir fi Isqath al-Tadbir, 'Unwan at-Tawfiq fi Adab al-Thariq, Tajul Arus al-Hawi li Tahzib al-Nufus, Miftah al-Falah wa Mishab al-Arwah fi Dzikrillah al-Karim al-Fattah, dan yang paling terkenal adalah kitabnya al-Hikam.
Saking populernya kitab al-Hikam tersebut, banyak ulama di Barat maupun Timur yang mensyarahinya, antara lain: Ibnu Abbad Muhammad bin Ibrahim ar-Randi (w. 792 H.), Syafiuddin bin Muhammad asy-Syadzili (w. 882 H.), Syaikh Zarruq Ahmad bin Muhammad al-Burnusi (w. 899 H.), dan Alauddin Ali bin Husamuddin (w. 975), Syeikh Al-Manawi Muhammad bin Abdurrauf (w. 1031 H.), Syeikh Syarqawi Abdullah bin Hijazai (w. 1227 H.), dan banyak lainnya.
Salah satu ajaran Ibnu Athaillah dalam kitab at-Tanwir fi Isqath al-Tadbir mengatakan: "engkau sering menghapus sifat wara' dalam dirimu lebih sering dari menghapus sifat lainnya. Engkau juga berusaha tidak tama' (berhasrat) pada makhluk. Seandainya engkau mensucikan diri dari sifat tama' dengan tujuh lautan pun, niscaya tetap tidak akan suci, kecuali engkau tidak lagi berharap pada manusia sedikit pun" (Ashim Ibrahim al-Kayyali, Athaillah as-Sakandari, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2013: 86).
Tentu saja, menghilangkan hasrat dan harapan pada kebaikan dan pertolongan makhluk (manusia) adalah hambatan dalam suluk. Seorang Salik sudah selayaknya menggantungkan diri pada Allah swt semata-mata. Tidak dibenarkan hati manusia dipenuhi ketergantungan pada selain Allah. Tentu saja hal itu sulit dilakukan, sehingga Ibnu Athaillah mengatakan bahwa hati tidak akan suci dari sifat tama’ sekalipun dicuci dengan tujuh samudera.
Ibnu Athaillah bukan saja ulama sufi yang berdakwah kepada umat biasa, melainkan juga sering berdakwah kepada para Sultan. Salah satu contohnya adalah percakapan antara Ibnu Athaillah dengan Sultan Mamluk Husamuddin Lajin. Pertemuan itu atas dasar undangan Sultan kepada Ibnu Athaillah yang sedang naik daun di tengah masyarakat muslim Mesir.
Kata Ibnu Athaillah, "ketika aku bersama Sultan Husamuddin Lajin, rahimahullah, aku lihat dia ingin sekali mendengar nasehatku. Sungguh aku bahagia, karena itu adalah kesempatan yang jarang aku bisa menyampaikan pandanganku. Saat itulah, pertama yang aku sampaikan padanya: hendaklah anda itu bersyukur pada Allah, karena Allah membuat pemerintahan anda itu penuh kedermawanan, sehingga semua rakyat menjadi lega karena anda. Dermawan itu adalah perkara yang sulit diusahakan oleh para raja dan sultan, berbeda dengan keadilan, suka memberi, dan kebaikan lainnya."
Sultan Husamuddin Lajin bertanya pada Ibnu Athaillah: "bagaimana saya harus bersyukur menurut Anda?" Ibnu Athaillah menjawab: "bersyukurkan dengan lisan, bersyukurkan dengan badan, dan bersyukurlah dengan hati." "Bagaimana saya bersyukur dengan tiga hal itu?," tanya Sultan.
Ibnu Athaillah menjabarkan: "syukur dengan lisan itu adalah hendaknya anda selalu mengingat-ignat nikmat yang Allah berikan. Syukur dengan badan itu adalah hendaknya anda menjalakan ibadah dan ketaatan pada Allah. Sedangkan syukur dengan hati itu hendaknya anda mengenal Allah, satu-satunya Pemberi kenikmatan".
Sultan Husamuddin Lajin kembali bertanya: “Bagaimana orang yang bersyukur itu dianggap telah bersyukur?” Ibnu Athaillah menerangkan: “apabila dia orang yang berilmu, maka ia akan mengajar, memberikan arahan, bimbingan, dan penjelasan.”
“Apabila dia itu termasuk orang yang kaya, maka syukurnya berupa berderma, memberi pertolongan dan mengutamakan kebutuhan orang lain. Dan apabila dia seorang penguasa, maka syukurnya berupa bertindak adil, menentang kezaliman, dan tidak menyengsarakan rakyat.” Saat itulah, Sultan Mamluk Husamuddin Lajin merasa sangat bahagia karena bertemu orang alim sekaliber Ibnu Athaillah (Samih Karim, A'lam fi Tarikh al-slam: Afkar li Tajdid wa Mawaqif li al-hayah, Dar al-Mishri al-Lubnaniah Kairo, 1995: 206).
Tentu saja, nasihat-nasihat Ibnu Athaillah tidak saja berkenaan bagaimana seseorang bisa mencapai Allah dengan ibadah, melainkan juga dengan kepedulian sosial seperti menolong orang yang membutuhkan, atau dengan kebijakan politik seperti menunjukkan keadilan, menolak kezaliman, dan tidak menyengsarakan rakyat. Semua nasehat Ibnu Athaillah di abad 13 itu masih relevan dengan zaman kita di abad 21 ini. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: