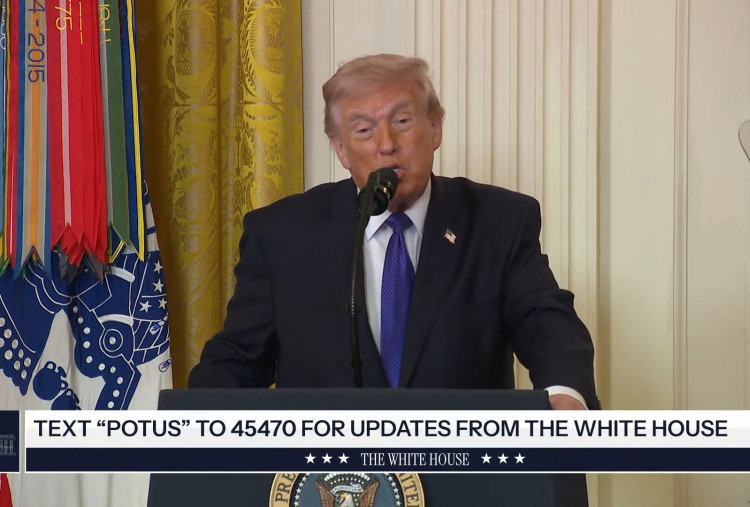Gus Yahya Dan Penolakan Politik Identitas yang Salah Tempat

KH Imam Jazuli Lc--
WACANA politik identitas memang selalu menarik dibahas. Topik terpentingnya persoalan identitas; terutama di dalam politik. Namun, dalam konteks apa politik identitas dimunculkan, itu juga tak kalah pentingnya. Identitas politik merupakan wacana yang muncul terkait pengalaman subjek. Di bawah struktur sosial yang ada, subjek mengalami ketidakadilan. Pada saat yang sama, subjek memiliki peluang besar untuk berbagi dan menjelaskan alternatif versi mereka sendiri.
Linda Martin Alcoff (2018) mencontohkan nasib korban kekerasan, baik KDRT atau seksual. Dalam situasi itu, struktur sosial memaksa pihak korban mengakui bahwa kejadian itu adalah sebab dirinya sendiri. Korban tidak diberi ruang membela kepentingan dan perspektifnya sendiri. Politik identitas bekerja untuk memahami kesenjangan penafsiran semacam itu. Berpihak pada yang tertindas, dan melawan penindasan maupun tekanan struktur sosial.
Diskursus politik identitas tidak bisa digiring ke luar dari spirit awal kemunculannya. Politik Identitas sejak awal berusaha memberikan panggung kepada suara-suara yang dibungkam. Politik identitas mengupayakan agar perspektif-perspektif alternatif bisa dihargai dan dihormati. Karenanya, Joan Scott (1992) mengatakan, politik identitas fokus pada transparansi pengalaman dan penyatuan interpretasinya. Dengan kata lain, politik identitas digunakan untuk menyatukan suara dalam mencari kebenaran pengalaman.
Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), tampak mengeluarkan makna politik identitas dari spirit kemunculannya. Pernyataannya itu disampaikan untuk melawan politik identitas, yang bermuara pada menjauhkan NU dan warga Nahdliyyin dari partai politik praktis. Pandangan ini didasarkan pada apa yang disebutnya sebagai hasil keputusan Muktamar PBNU tahun 1984, yang ingin kembali pada Khitah 1926 dengan tidak ikut tampil dalam perebutan kekuasaan.
Jika benar begitu tujuan utamanya, Gus Yahya sedang memutarbalikkan makna politik identitas. Dari yang semula untuk memberikan ruang bagi suara-suara alternatif di tengah struktur sosial yang tidak adil. Menjadi menutup ruang bagi warga Nahdliyyin untuk tampil di kancah kekuasaan politik. Sehingga hanya akan ada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dari kalangan Nahdliyyin, yang pernah berada di puncak kekuasaan. Selebihnya, warga Nahdliyyin tidak memiliki peluang, khususnya dukungan penuh dari PBNU.
Baiklah. Anggap saja pandangan Gus Yahya sebagai ketum PBNU didasarkan pada keputusan Muktamar 1984 untuk kembali ke Khitah. Namun, hal itu hanya satu pengalaman Nahdliyyin dari banyak pengalaman lainnya yang berbeda. Katakanlah pada tahun 1998, Kiai-kiai dan santri Nahdliyyin mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ini adalah pengalaman lain yang berbeda. Menurut paradigma Joan Scott, interpretasi pengalaman yang berbeda-beda ini harus disatukan (univokal). Inilah politik identitas.
Pada kenyataannya, Gus Yahya (GY) tampak tidak berupaya untuk menyatukan keragaman interpretasi atas pengalaman-pengalaman Nahdliyyin di tahun 1984 dan 1998. GY hanya berfokus untuk mengambil jalan anti-politik praktis dan tidak menerima kenyataan pengalaman para kiai NU berpolitik praktis, baik atas nama ormas NU maupun atas nama keputusan personal mereka. Misalnya, tatkala PBNU dipimpin KH Said Aqil Siroj, kanalisasi suara warga NU pada paslon Jokowi-Ma’ruf Amin.
Anggap saja pendapat GY untuk anti-politik praktis itu benar, dengan menawarkan alternatif lain berupa politik kebangsaan. Pertanyaannya, apakah alternatif lain tersebut jauh lebih baik? Kita perlu ingat sekali lagi pandangan Francis Fukuyama (2018) dalam menggambarkan praktik politik identitas di Amerika. Menurutnya, politik identitas di Amerika dilakukan dengan cara mengabaikan ketimpangan ekonomi di sebelah kiri dan menawarkan alternatif lain yang bisa melupakan ketimpangan tersebut di sebelah kanan.
Jika itu terjadi, sikap GY untuk melawan politik identitas terjebak dalam bentuk praktik politik identitas lain yang lebih mengerikan. Politik kebangsaan yang anti-politik praktis tersebut sama saja dengan mengabaikan ketimpangan sosial-politik di sebelah kiri, dan menawarkan alternatif lain yang bisa melupakan ketimpangan tersebut. Sebab, pada kenyataannya, sejak Pemilu 1955 sampai 2019 kemarin, tidak sekalipun wakil dari Nahdliyyin (kaum santri) yang berhasil menjabat sebagai Presiden, kecuali Gus Dur.
Kenyataan pahit yang dialami oleh warga Nahdliyyin tersebut, yaitu ketimpangan kesempatan sebagai presiden, berusaha dilupakan oleh GY dengan menawarkan istilah baru yang disebutkan sebagai politik kebangsaan. Lebih-lebih GY menjadikan pemikiran Gus Dur sebagai sandarannya. Padahal, Gus Dur sendiri satu-satunya representasi warga Nahdliyyin yang menjadi presiden. Seandainya Gus Dur tidak pernah menjadi presiden, maka politik kebangsaan yang menjauhi politik praktis dan anti-politik identitas itu masih bisa diterima oleh akal sehat.
Penulis berpandangan, perlawanan terhadap politik identitas seperti bumerang dan paradoks. Di satu sisi, sikap anti-politik identitas dan politik praktis merupakan tindakan mengeluarkan makna politik identitas dari konteks dan spirit utamanya. Di sisi lain, politik kebangsaan sebagai alternatif politik kekuasaan adalah politik identitas itu sendiri. Sayangnya, politik identitas ini seakan-akan untuk melupakan kenyataan pahit lain, yang lebih nyata dan terang-benderang di depan mata. Yaitu, tak adanya representasi Nahdliyyin atau Santri sebagai Presiden RI selain Gus Dur. Wallahu a’lam bis showab. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: